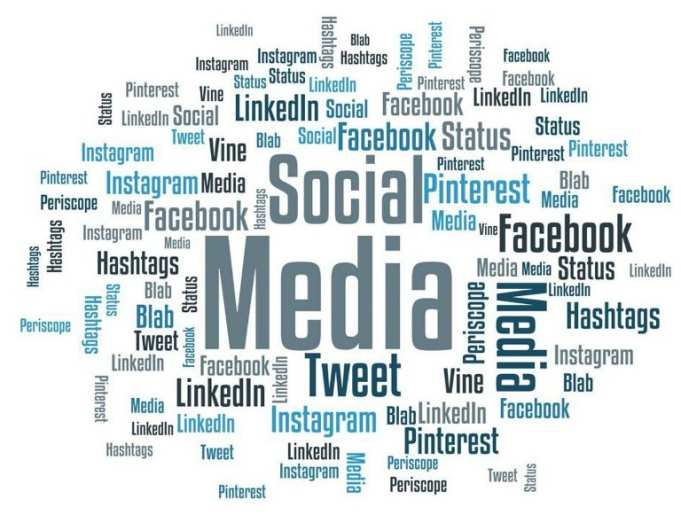Oleh: Amir Machmud NS
 MASIH relevankah para pekerja pers dan akademisi Ilmu Komunikasi berbicara kencang tentang netralitas media, utamanya setiap menjelang kontestasi politik, seperti hari-hari ini?
MASIH relevankah para pekerja pers dan akademisi Ilmu Komunikasi berbicara kencang tentang netralitas media, utamanya setiap menjelang kontestasi politik, seperti hari-hari ini?
Masih tercetak dalam pikiran, menjelang Pemilu 2019 saya menjadi narasumber diskusi di LPP RRI Semarang bersama akademisi Ilmu Komunikasi dari sebuah perguruan tinggi.
Kesimpulan dari diskusi tersebut, menurut saya mengulang-ulang apa yang sudah sering tersampaikan, yakni ide das sollen: antara yang ada dalam pikiran teoretik akademisi dengan hamparan das sein dalam mindset kerja yang dihadapi praktisi.
Posisi idealistis wartawan dan media, di mata akademisi, tak boleh terkontaminasi oleh intervensi faktor apa pun dalam ekosistem media, baik yang terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebaliknya, walaupun mendapatkan doktrin tentang filosofi “pagar api”, para praktisi media tak mungkin menomorsekiankan tujuan bisnis yang secara nyata berhubungan dengan biaya produksi media.
Ya, bagaimana menggaransi keberlangsungan konsistensi memperjuangkan idealisme media jika tidak ditopang oleh “jaminan hidup” dari kontraprestasi wartawan dan redaktur yang diterima dari perusahaannya?
Dan, kira-kira selalu begitulah pusaran kesimpulan dari setiap diskusi tentang persoalan netralitas media. Terhampar semacam “kerumitan di lorong gelap”. Padahal, dari catatan perjalanan kemerdekaan pers, sejauh ini, bahkan orang-orang media sendiri pun pernah merasa “terlukai” oleh pengambilan posisi sejumlah media secara gamblang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada media yang mendukung calon presiden-calon wakil presiden kontestan Pilpres 2014 dan 2019.
Bukankah ini berarti, intensi ketidaknetralan secara telanjang tidak bisa disikapi sebagai positioning rutin yang biasa-biasa saja? Di tengah arus bisnis dalam industri media, bagaimanapun masih tersisa ruang keterusikan nuraniah yang memaparkan kenyataan, bahwa tak sedikit wartawan dan media yang memilih membangun keseimbangan dengan mencoba berada di tengah-tengah.
Kemeruyakan Media Sosial
Pemilihan Umum 2024 berada dalam bingkai waktu bersambungan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024. Bahkan, sebagai ungkapan sikap menyukseskan perhelatan nasional demokrasi tersebut PWI Pusat mengundurkan waktu puncak acara, dari 9 Februari menjadi 20 Februari 2024. Tema HPN juga edukatif, “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.
HPN kali ini bersinggungan dengan momentum kemeruyakan media sosial dalam mengunggah produk olahan informasi berupa opini, kontra-opini, analisis fakta kejadian, yang ter-framing dari sisi kepentingan pemroduksi dan pemilik akun. Persebaran konten-konten media sosial ini saling bersahutan dengan sajian media-media mainstream. Terkait dengan isu-isu pemilu, terkadang sulit dibedakan mana produk jurnalistik media massa dengan unggahan media sosial.
Tentu tidak mungkin menuntut konten-konten media sosial agar diproduksi dengan kualifikasi akuntabilitas dan standar verifikasi jurnalistik. Mereka memiliki parameter sendiri, dengan pertanggungjawaban sosial dan konsiderans hukum tersendiri. Mereka bergerak tidak dengan menggunakan landasan fungsi media seperti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tak pula dengan penghayatan asas-asas moralitas berbasis Kode Etik Jurrnalistik.
Konten-konten yang diunggah rata-rata merupakan isu aktual — terutama yang berkualifikasi kontroversial — pemilu. Produknya jelas berpihak, karena membawa perspektif kepentingan tertentu yang telah di-setting dan di-framing sesuai dengan pilihan sikap pemilik akun.
Dalam pijakan tujuan pemviralan isu tertentu, nyaris tak ada perbedaan cara antara media mainstream dengan media sosial. Dasar pemikirannya kurang lebih sama, yakni eksplorasi persoalan, kreasi pengembangan, mencari celah faktor pembeda, dan strategi penyuburan (pemviralan).
Penyeimbangan verifikatif dilakukan dengan pola-pola segmentasi sajian yang konfliktif. Saya menyebutnya sebagai semacam genre “conflict-tainment”: konflik yang diolah menjadi hiburan dalam sajian media, atau konten persengketaan yang disajikan dengan narasi magnetis.
Di ranah media massa, pikiran dan strategi pemviralan ini terhubung dengan kepentingan algoritma google. Ujung-ujungnya adalah upaya meraup google adsense. Teknik mengunyah-unyah informasi viral merupakan pilihan kreativitas setting isu publik yang terus diproduksi dan direproduksi.
Praktik-praktik berjurnalistik dan bermedia dalam konteks “ideologi viralitas” ini, sepintas memang tak terlihat berkaitan langsung dengan persoalan netralitas media. Namun dalam berbagai isu pilpres, misalnya, setting dan pembingkaian informasi apa pun bisa tersuburkan sebagai ungkapan dan orientasi pendukungan calon tertentu. Atau sebaliknya, kebijakan newsroom media bisa memasifikasikan sebagai sikap kontra, berupa instrumen pencitraan buruk untuk calon lainnya.
Ajaran Relevan tentang Kualitas
Jadi masih relevankah diskusi-diskusi tentang netralitas media (mainstream), ketika publik leluasa bisa mengakses aneka platform media sosial untuk memenuhi hasrat representasi keberpihakan mereka?
Dalam hal netralitas, media bagai berada di lorong sikap yang rumit. Bakal sia-siakah sikap netral dalam mengawal sebuah kontestasi politik seperti Pilpres 2024 ini, karena andai benar-benar memosisikan diri berada di tengah-tengah secara independen pun, bakal tak berdaya menghadapi kemeruyakan arus konten berpihak media sosial?
Ajaran tentang sikap das sollen dan das sein dalam memahami filosofi “pagar api” tampaknya perlu bergeser ke arah ajaran tentang kualitas konten jurnalistik. Segala sesuatu yang terkait dengan sajian media, harus terukur dari sisi “kepentingan publik”. Sisi ini akan menjadi sikap mulia yang memberi kekuatan kualitatif bagi produk-produk jurnalistik.
Ya, untuk apa kita mengunggah informasi? Tentu agar publik memercayai informasi yang kita sampaikan.
Bagaimana agar informasi kita dipercaya oleh publik? Informasi itu harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
Seperti apakah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan itu? Informasi itu harus memenuhi mekanisme verifikasi yang berdisiplin.
Pada titik kepercayaan publik, sikap akuntabel, dan disiplin verifikasi sebagai syarat kualitatif itulah kita memosisikan netralitas sebagai sikap.
Kualitas akan lahir dari proses, bentuk olahan (kemasan), dan kemauan penghayatan etis. Yang akan lahir adalah estetika dan eksotika jurnalistik. Estetis, karena memenuhi standar keseimbangan teknis, dan selanjutnya eksotis karena memenuhi standar kualifikasi mutu sajian.
— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fiskom UKSW —